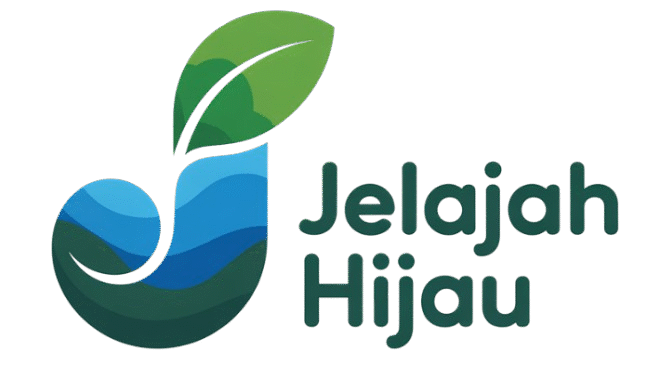jelajahhijau.com Lonjakan bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Indonesia, khususnya Sumatera, telah menelan korban jiwa dalam jumlah yang mengkhawatirkan. Angka kematian yang terus bertambah tidak bisa lagi dipandang sebagai konsekuensi alamiah semata. Di balik setiap banjir bandang dan tanah longsor, terdapat rangkaian keputusan politik dan ekonomi yang telah lama mengabaikan daya dukung lingkungan.
Deforestasi masif, alih fungsi lahan tanpa kendali, serta ekspansi industri ekstraktif menjadi faktor utama yang memperparah kerentanan wilayah. Ketika hutan penyangga hilang, hujan yang semestinya menjadi berkah justru berubah menjadi ancaman mematikan.
Kerugian Ekonomi yang Menggerus Masa Depan
Dampak bencana ekologis tidak berhenti pada hilangnya nyawa manusia. Kerusakan infrastruktur, lumpuhnya aktivitas ekonomi, serta hilangnya sumber penghidupan masyarakat menimbulkan kerugian ekonomi dalam skala besar. Triliunan rupiah lenyap hanya dalam hitungan waktu singkat akibat banjir dan longsor yang berulang.
Ironisnya, kerugian ini sering kali jauh lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi jangka pendek dari pembukaan lahan atau eksploitasi sumber daya alam. Namun perhitungan semacam ini jarang menjadi pertimbangan utama dalam proses pengambilan kebijakan.
Respons Publik yang Berulang dan Dangkal
Setiap kali bencana terjadi, pola respons publik cenderung sama. Gelombang solidaritas muncul melalui penggalangan donasi, relawan berdatangan, dan pejabat publik mengunjungi lokasi terdampak dengan pernyataan keprihatinan. Media sosial dipenuhi perdebatan, simpati, dan kemarahan.
Namun setelah masa darurat berlalu dan sorotan media berpindah, diskursus serius pun ikut menghilang. Akar persoalan di hulu jarang disentuh secara mendalam. Pertanyaan tentang izin konsesi, tata ruang, dan akuntabilitas kebijakan nyaris tak mendapat ruang yang sepadan.
Politik Lingkungan yang Kehilangan Daya Gugat
Di sinilah persoalan utama muncul: absennya oposisi hijau yang kuat dalam arena politik, khususnya di parlemen. Isu lingkungan sering kali tersisih oleh agenda ekonomi jangka pendek dan kompromi politik. Tidak banyak aktor politik yang secara konsisten menjadikan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama.
Tanpa kekuatan politik yang mampu menggugat kebijakan eksploitatif, regulasi lingkungan mudah dilonggarkan. Evaluasi izin konsesi berjalan lambat, sementara kerusakan terus berlanjut di lapangan.
Parlemen dan Kekosongan Representasi Hijau
Parlemen seharusnya menjadi ruang utama untuk memperjuangkan kepentingan publik jangka panjang, termasuk keselamatan ekologis. Namun dalam praktiknya, suara lingkungan sering kalah oleh kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang sempit.
Ketiadaan fraksi atau blok politik yang secara tegas mengusung agenda hijau membuat isu lingkungan kehilangan daya tawar. Akibatnya, kebijakan mitigasi bencana dan adaptasi iklim berjalan setengah hati, lebih reaktif daripada preventif.
Deforestasi dan Alih Fungsi Lahan sebagai Akar Masalah
Berbagai kajian menunjukkan bahwa deforestasi dan alih fungsi lahan berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya intensitas bencana. Hutan yang berfungsi sebagai penyerap air dan penahan tanah digantikan oleh perkebunan monokultur atau kawasan industri.
Ketika curah hujan tinggi, wilayah yang kehilangan tutupan hutan tidak mampu lagi menahan air. Sungai meluap, lereng runtuh, dan pemukiman di hilir menjadi korban. Pola ini terus berulang, namun jarang diiringi evaluasi kebijakan yang tegas.
Mitigasi yang Kalah oleh Kepentingan Jangka Pendek
Secara konseptual, mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan telah lama menjadi bagian dari agenda pembangunan. Namun implementasinya sering kalah oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. Proyek-proyek yang merusak lingkungan tetap berjalan dengan dalih penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah.
Sayangnya, biaya sosial dan ekologis dari kebijakan semacam ini jauh lebih besar dan bersifat jangka panjang. Beban akhirnya ditanggung masyarakat, terutama kelompok rentan yang tinggal di wilayah rawan bencana.
Krisis Iklim sebagai Krisis Tata Kelola
Bencana ekologis yang terus berulang sejatinya mencerminkan krisis tata kelola. Lemahnya pengawasan, tumpang tindih regulasi, serta minimnya transparansi dalam pemberian izin memperparah situasi. Krisis iklim tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan krisis politik dan kelembagaan.
Tanpa reformasi tata kelola yang serius, upaya mitigasi hanya akan menjadi slogan. Perlindungan lingkungan membutuhkan keberanian politik untuk meninjau ulang kebijakan yang merugikan ekosistem.
Urgensi Membangun Oposisi Hijau
Ke depan, kehadiran oposisi hijau di parlemen menjadi semakin mendesak. Bukan sekadar simbol, tetapi kekuatan politik yang mampu mengawal kebijakan lingkungan secara konsisten dan kritis. Oposisi hijau berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan mempertimbangkan dampak ekologisnya.
Tanpa tekanan politik yang kuat, isu lingkungan akan terus berada di pinggiran agenda nasional. Padahal, keselamatan ekologis merupakan fondasi utama keberlanjutan ekonomi dan sosial.
Kesimpulan: Ketika Alam Menagih Tanggung Jawab Politik
Bencana ekologis yang merenggut nyawa dan melumpuhkan ekonomi bukanlah kejadian acak. Ia adalah konsekuensi dari pilihan kebijakan yang mengabaikan keseimbangan lingkungan. Selama politik lingkungan tidak memiliki suara yang kuat di parlemen, pola kerusakan akan terus berulang.
Sudah saatnya krisis iklim dipahami sebagai krisis politik. Tanpa oposisi hijau yang berani dan konsisten, mitigasi bencana hanya akan menjadi reaksi sesaat. Alam terus memberi peringatan, dan pertanyaannya kini bukan lagi apakah kita mampu merespons, melainkan apakah kita bersedia mengubah arah kebijakan sebelum semuanya terlambat.

Cek Juga Artikel Dari Platform georgegordonfirstnation.com