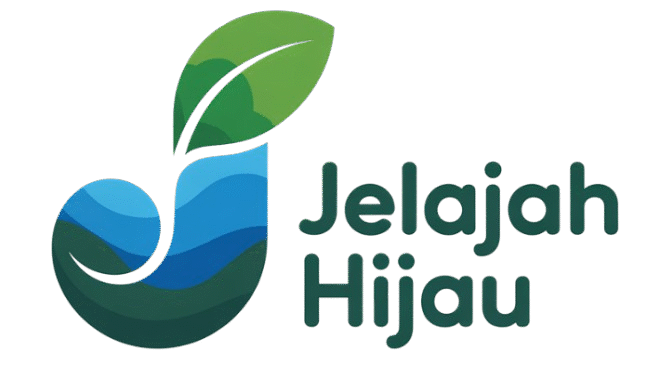Hutan yang Tumbuh Ratusan Tahun, Runtuh Sekejap
Hutan tidak lahir dalam satu musim. Ia tumbuh perlahan, melalui ratusan tahun interaksi antara tanah, air, cahaya, dan makhluk hidup yang saling menopang. Setiap lapisan tanah menyimpan sejarah, setiap pohon memegang peran dalam menjaga keseimbangan. Namun semua proses panjang itu dapat runtuh hanya dalam hitungan bulan, bahkan hari, ketika mesin dan kapak bekerja tanpa kendali.
Kini, hutan itu bukan hanya botak. Ia sudah menjadi gundul. Tidak ada lagi kanopi hijau yang memayungi tanah, tidak tersisa akar-akar kuat yang menahan air hujan. Yang tampak hanyalah hamparan batang pohon tumbang, tersusun horizontal seperti barisan kayu gelondongan yang menunggu diangkut. Pemandangan ini tidak menghadirkan rasa kagum, melainkan kesedihan yang dalam.
Dari Botak Menuju Gundul Total
Bukan hanya botak, ribuan hektar hutan itu kini rata. Pinus, jati, meranti, dan berbagai pohon keras lainnya ditebas tuntas tanpa sisa. Tidak ada lagi seleksi, tidak ada jeda. Semua diratakan atas nama kebutuhan dan keuntungan. Ranting dan daun yang dahulu membentuk ekosistem kecil kini meranggas, membusuk di atas tanah yang terpapar langsung panas matahari.
Istilah “botak” seolah sudah tidak cukup menggambarkan kondisi ini. Botak masih menyisakan harapan tumbuh kembali. Gundul adalah tahap lanjut, ketika hutan kehilangan hampir seluruh kemampuannya untuk memulihkan diri secara alami. Tanah mengeras, mikroorganisme mati, dan benih yang tersisa kesulitan tumbuh.
Hujan yang Menjadi Ancaman
Ketika hujan turun deras, hutan yang gundul tidak lagi mampu menahan air. Tidak ada akar yang mengikat tanah, tidak ada serasah daun yang menyerap limpahan hujan. Air meluncur bebas, membawa tanah, lumpur, dan bebatuan menuju sungai-sungai.
Sungai yang dulu mengalir tenang berubah menjadi arus liar. Debit air melonjak dalam waktu singkat, menghantam tebing dan bantaran. Hujan yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru menjelma ancaman. Semua ini bukan fenomena alam semata, melainkan akibat langsung dari hilangnya penyangga ekologis.
Desa-Desa yang Membayar Harga Mahal
Dampak penggundulan hutan tidak berhenti di kawasan hulu. Di hilir, puluhan desa harus menanggung akibatnya. Rumah-rumah terendam, jembatan runtuh, ladang rusak, dan bukit-bukit longsor tanpa peringatan. Kayu-kayu gelondongan bekas tebangan ikut hanyut, menghantam apa saja yang dilewatinya.
Ironisnya, masyarakat yang menjadi korban adalah mereka yang paling sedikit menikmati hasil eksploitasi. Mereka tidak memperoleh keuntungan dari kayu, tidak terlibat dalam perhitungan ekonomi, tetapi harus menanggung risiko paling besar. Isak tangis, kehilangan, dan ketidakpastian menjadi bagian dari keseharian mereka.
Ke Mana Para Pemodal Itu Pergi
Pertanyaan yang terus bergema adalah: ke mana para pemodal yang menikmati keuntungan dari hutan itu? Ketika bencana datang, tidak ada wajah yang muncul untuk bertanggung jawab. Yang ada justru keheningan yang terasa seragam. Semua seolah sepakat untuk bungkam, menutup mata, dan melanjutkan rutinitas.
Dalam keheningan itulah, kejahatan ekologis menemukan ruang aman. Tanpa tekanan sosial yang kuat, tanpa penegakan hukum yang tegas, penggundulan hutan terus berulang. Pelaku berganti, modus berubah, tetapi pola kerusakannya tetap sama.
Kerusakan yang Dinormalisasi
Penggundulan hutan yang terjadi berulang kali perlahan membentuk kebiasaan berbahaya. Masyarakat dipaksa terbiasa melihat hutan hilang, sungai meluap, dan desa tenggelam. Tragedi demi tragedi berubah menjadi berita rutin yang cepat dilupakan.
Normalisasi ini berbahaya karena merusak kepekaan kolektif. Ketika kerusakan dianggap wajar, tuntutan untuk perubahan melemah. Botak menjadi gundul, gundul menjadi statistik, dan statistik menjadi sekadar angka tanpa empati.
Lebih dari Sekadar Kerusakan Fisik
Hutan yang gundul bukan hanya persoalan lanskap. Ia adalah simbol runtuhnya hubungan manusia dengan alam. Ketika hutan diperlakukan semata sebagai komoditas, nilai kehidupan yang dikandungnya terhapus dari pertimbangan.
Kerusakan ini juga meninggalkan luka sosial. Konflik lahan, kemiskinan akibat hilangnya sumber penghidupan, hingga migrasi paksa menjadi konsekuensi lanjutan. Semua ini tidak pernah masuk dalam kalkulasi keuntungan, tetapi nyata dirasakan oleh masyarakat.
Antara Seruan Lestari dan Kenyataan
Seruan “lestari” kerap digaungkan dalam berbagai forum dan slogan. Namun kenyataan di lapangan sering menunjukkan hal sebaliknya. Selama keuntungan jangka pendek lebih diutamakan daripada keberlanjutan, selama penegakan hukum lemah, kata lestari hanya menjadi hiasan retorika.
Hutan tidak hanya botak, ia sudah gundul. Dan kegundulan itu mencerminkan kegagalan kolektif dalam menjaga amanah alam. Tanpa keberanian untuk menghentikan eksploitasi brutal, menindak pelaku, dan memulihkan kerusakan, cerita duka ini akan terus diwariskan.
Menolak Diam, Merawat Harapan
Di tengah kegundulan, harapan masih mungkin tumbuh jika ada keberanian untuk berubah. Menolak diam, menolak bungkam, dan terus mengingatkan bahwa hutan bukan warisan dari leluhur, melainkan titipan untuk generasi mendatang.
Jika hutan terus digunduli, yang tersisa bukan hanya tanah tandus, tetapi masa depan yang rapuh. Dan saat itu tiba, tidak ada denda, tidak ada keuntungan, yang mampu menggantikan apa yang telah hilang.
Baca Juga : Ironi Penegakan Hukum Ekologi dan Denda Kerusakan
Jangan Lewatkan Info Penting Dari : marihidupsehat