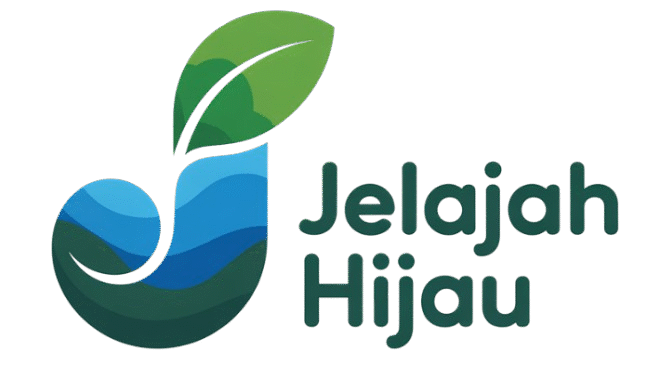jelajahhijau.com Gelombang bencana hidrometeorologi di Sumatera telah berubah menjadi tragedi kemanusiaan berskala besar. Ribuan nyawa melayang, ratusan ribu warga kehilangan tempat tinggal, dan kerugian ekonomi mencapai puluhan triliun rupiah. Angka-angka ini bukan sekadar statistik tahunan, melainkan cermin dari kegagalan struktural dalam mengelola lingkungan dan risiko bencana.
Intensitas banjir bandang dan longsor yang terjadi berulang kali memperlihatkan bahwa krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan. Ia telah hadir di depan mata, dipercepat oleh deforestasi, alih fungsi lahan, dan eksploitasi sumber daya alam yang melampaui daya dukung ekosistem.
Kerusakan Lingkungan dan Biaya yang Harus Dibayar
Kerugian ekonomi akibat bencana ekologis menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan moral atau ekologi, tetapi juga persoalan ekonomi nasional. Infrastruktur rusak, aktivitas produksi terhenti, dan anggaran negara tersedot untuk penanganan darurat yang seharusnya bisa dicegah melalui mitigasi jangka panjang.
Ironisnya, biaya pemulihan pascabencana sering kali jauh lebih besar dibandingkan investasi untuk pencegahan. Namun, logika kebijakan masih cenderung reaktif. Negara bergerak cepat saat bencana terjadi, tetapi lambat dalam memperbaiki akar masalah yang menyebabkannya.
Ritual Krisis yang Terus Berulang
Respons publik dan negara terhadap bencana kerap mengikuti pola yang sama. Donasi digalang, pejabat datang ke lokasi dengan narasi empati, dan media sosial dipenuhi diskusi emosional. Semua terlihat sibuk dan peduli, setidaknya untuk sementara waktu.
Namun, ketika fase darurat berakhir, perhatian pun menghilang. Tidak ada tekanan politik berkelanjutan untuk meninjau ulang izin konsesi, mengevaluasi tata ruang, atau menghentikan praktik eksploitasi yang merusak lingkungan di wilayah hulu. Bencana berlalu, tetapi kebijakan tetap berjalan seperti sebelumnya.
Parlemen yang Minim Agenda Hijau
Di sinilah persoalan utama muncul. Parlemen, sebagai lembaga politik tertinggi yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan, terlihat minim inisiatif dalam isu lingkungan. Hampir tidak ada oposisi hijau yang secara konsisten mengawal kebijakan ekologis dan menantang keputusan pemerintah yang berpotensi merusak lingkungan.
Isu lingkungan sering kali tenggelam di antara agenda politik jangka pendek. Debat anggaran, kalkulasi elektoral, dan kepentingan industri lebih dominan dibandingkan diskursus tentang keberlanjutan dan keselamatan ekologis.
Lingkungan sebagai Isu Pinggiran Politik
Dalam praktiknya, isu lingkungan masih dianggap sebagai isu tambahan, bukan arus utama kebijakan. Padahal, dampak krisis iklim bersifat lintas sektor: ekonomi, kesehatan, pangan, hingga stabilitas sosial. Ketika lingkungan rusak, seluruh sendi kehidupan ikut terguncang.
Absennya oposisi hijau membuat kebijakan lingkungan berjalan tanpa pengawasan kritis. Keputusan strategis seperti pemberian izin tambang, perkebunan skala besar, dan proyek infrastruktur sering kali lolos tanpa kajian ekologis yang ketat atau debat publik yang memadai.
Deforestasi dan Alih Fungsi Lahan sebagai Akar Masalah
Bencana hidrometeorologi di Sumatera tidak dapat dilepaskan dari masifnya deforestasi dan alih fungsi lahan. Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga air dan pengendali erosi berubah menjadi area konsesi ekonomi. Ketika hujan ekstrem datang, alam tidak lagi mampu menahan beban.
Tanpa tekanan politik yang kuat, praktik ini terus berlangsung. Parlemen jarang memanggil pemegang konsesi untuk dimintai pertanggungjawaban atas dampak ekologis dari aktivitas mereka.
Kegagalan Mitigasi sebagai Masalah Sistemik
Mitigasi bencana seharusnya menjadi prioritas utama negara. Namun, selama pendekatan pembangunan masih bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, mitigasi hanya menjadi jargon kebijakan. Peta risiko diabaikan, tata ruang dilanggar, dan rekomendasi ilmiah sering kali tidak diindahkan.
Krisis ini bersifat sistemik, bukan kebetulan. Tanpa perubahan arah kebijakan, bencana serupa akan terus berulang dengan skala yang semakin besar.
Mengapa Oposisi Hijau Penting
Oposisi hijau bukan berarti anti-pembangunan. Sebaliknya, ia berfungsi sebagai penyeimbang agar pembangunan berjalan secara berkelanjutan. Kehadiran suara kritis di parlemen penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi mempertimbangkan dampak ekologis dan sosialnya.
Negara-negara dengan politik lingkungan yang kuat menunjukkan bahwa transisi hijau justru membuka peluang ekonomi baru. Energi terbarukan, ekonomi sirkular, dan restorasi ekosistem dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus mengurangi risiko bencana.
Peran Publik dalam Menekan Agenda Lingkungan
Ketika parlemen absen, tekanan publik menjadi kunci. Masyarakat sipil, akademisi, dan media memiliki peran penting untuk menjaga isu lingkungan tetap hidup dalam ruang publik. Diskursus tidak boleh berhenti pada empati sesaat saat bencana terjadi.
Tekanan yang konsisten dapat memaksa aktor politik untuk menjadikan isu lingkungan sebagai agenda utama, bukan sekadar pelengkap retorika.
Menuju Politik Lingkungan yang Serius
Krisis iklim menuntut perubahan paradigma politik. Lingkungan harus diposisikan sebagai fondasi kebijakan, bukan hambatan pembangunan. Parlemen perlu didorong untuk melahirkan regulasi yang tegas, transparan, dan berpihak pada keberlanjutan.
Tanpa oposisi hijau yang kuat, kebijakan lingkungan akan terus kalah oleh kepentingan jangka pendek.
Kesimpulan
Bencana ekologis di Sumatera adalah peringatan keras bahwa krisis iklim telah berada pada tahap darurat. Ribuan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang masif menunjukkan kegagalan mitigasi dan lemahnya perlindungan lingkungan.
Absennya oposisi hijau di parlemen memperparah situasi. Tanpa pengawasan politik yang serius, akar masalah seperti deforestasi dan alih fungsi lahan akan terus diabaikan. Jika politik tidak segera berubah, bencana serupa bukan lagi kemungkinan, melainkan keniscayaan yang terus berulang.

Cek Juga Artikel Dari Platform carimobilindonesia.com